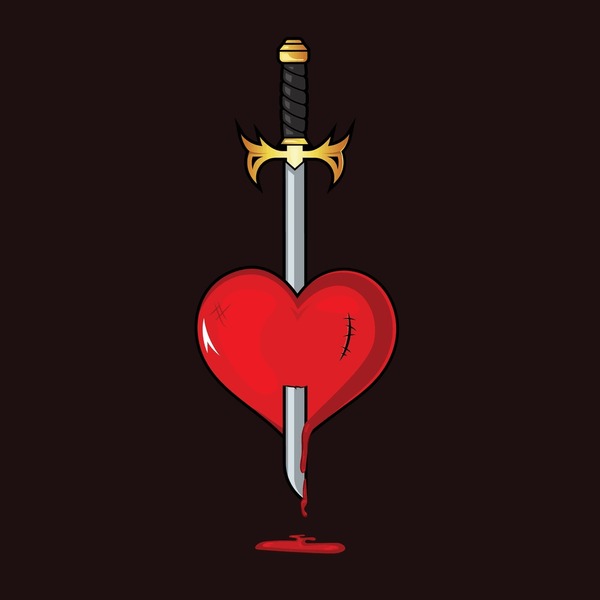Di banyak negeri, dari pasar unta hingga gedung parlemen, ada satu barang dagangan yang tidak pernah kehabisan peminat: darah suci.
Entah itu darah nabi, darah dewa, darah raja, atau darah keramat yang entah disuling dari mana, manusia tampaknya punya bakat alami untuk percaya bahwa kehormatan bisa diwariskan lewat pembuluh darah — semacam warisan genetik untuk kemuliaan.
Di Indonesia, kita menyaksikan musim semi baru: berebut klaim sebagai keturunan Rasul. Nama-nama bersanad panjang diarak dengan bangga seperti piagam kelulusan dari universitas langit. Sebagian besar tanpa perlu dibuktikan, tanpa perlu diuji. Cukup diumumkan, dan dunia diminta berlutut.
Tapi sebelum kita terlalu terharu, ada baiknya kita melihat ke belakang: manusia di seluruh dunia memang sudah lama bermain dalam bisnis ini.
Panggung Lama: Ketika Darah Menjadi Mata Uang
Di Afrika Utara, sebuah dinasti bernama Fatimiyah berdiri gagah pada abad ke-10. Modal utama mereka? Klaim sebagai keturunan putri Nabi. Dengan darah itu, mereka membeli kekuasaan, memungut pajak, mendirikan negara.
Ratusan tahun kemudian, di Maroko, keluarga Alawiyah memanfaatkan klaim darah Hasan bin Ali untuk mendirikan dinasti. Raja Maroko hari ini, bahkan di zaman jet pribadi dan Wi-Fi, masih menjual legitimasi yang dikemas dalam botol antik bernama “darah suci”.
Yaman juga punya ceritanya sendiri. Para imam di sana tidak cukup puas bertarung gagasan. Mereka bertarung silsilah, adu siapa yang lebih kental darah kenabiannya. Bila perlu, membasahi tanah dengan darah baru agar silsilah tetap relevan.
Di Indonesia, versi kita lebih halus. Tidak ada perang fisik. Hanya lobi halus di balik layar, kartu nama bercorak Timur Tengah, dan selfie di depan makam leluhur. Era baru aristokrasi spiritual: lebih bersih, lebih harum, lebih bisa dikirim lewat kurir kilat.
Panggung Dunia: Semua Orang Ingin Sedikit Darah Tuhan
Tentu saja, ini bukan monopoli dunia Islam.
Di Eropa Abad Pertengahan, para raja mengklaim bahwa Tuhan sendiri mengetuk pintu kamar tidur nenek moyang mereka dan menitipkan mandat suci. Sejak itu, keturunan mereka — betapapun bodoh, kejam, atau korup — diberi hak ilahi untuk memungut pajak dan memulai perang.
Di Jepang, Kaisar dianggap cucu dari Dewi Matahari. Ini memberi mereka kekebalan moral. Membom negara lain? Membakar kota tetangga? Ah, itu urusan manusia biasa. Darah dewa terlalu suci untuk ikut bertanggung jawab.
Di China, Kaisar dinobatkan sebagai “Putra Langit”. Bila rakyat menderita kelaparan, itu tandanya Langit mencabut mandat. Tapi sampai itu terjadi? Kaisar bebas hidup dengan 3000 selir dan perbendaharaan emas lebih berat dari hukum moral.
Afrika juga punya kisahnya. Para raja mengaku sebagai titisan roh agung. Dengan klaim itu, mereka mengikat rakyat dalam takhayul yang rapi dan mengubah negeri menjadi teater sakral di mana sang raja selalu berperan sebagai tokoh utama — sekalipun ceritanya sudah basi.
Kenapa Manusia Suka Darah Suci?
Mungkin karena bekerja itu berat.
Membuktikan diri lewat kerja keras, ide, integritas? Terlalu melelahkan. Lebih praktis mengaku sebagai cicit ketiga belas dari seseorang yang suci. Darah adalah shortcut sosial. Semacam “bypass” yang melompati semua kerumitan meritokrasi.
Darah juga enak untuk diwariskan. Jika kekuasaan didasarkan pada kemampuan, maka setiap generasi harus berjuang ulang. Tapi jika kekuasaan didasarkan pada darah, maka cukup melahirkan anak dan memastikan akta kelahiran cukup tebal untuk mengesankan keturunan.
Bahkan masyarakat modern yang mengaku mencintai demokrasi diam-diam masih memelihara naluri purba ini. Lihat saja bagaimana orang berebut foto dengan “habib”, “putra raja”, “cicit pahlawan”, bahkan “mantan presiden”. Merek dagang darah masih laku keras.
Darah yang Tak Menjamin Apa-Apa
Tapi sejarah punya cara lucu untuk mengingatkan kita.
Banyak dari mereka yang mengaku berdarah suci justru berakhir menjadi lelucon sejarah. Raja-raja suci yang dijatuhkan oleh rakyat lapar. Imam-imam keramat yang diusir oleh generasi bosan. Kaisar langit yang ditelanjangi oleh badai zaman.
Darah suci, jika tidak disertai kemampuan, integritas, dan kerja nyata, hanyalah tinta merah dalam buku cerita yang akan cepat mengering.
Anehnya, manusia selalu berhasil melupakan pelajaran ini. Setiap kali darah lama gagal, kita hanya butuh sedikit rebranding, mungkin sedikit parfum Timur Tengah atau segel lilin kuno, lalu kita mulai lagi: percaya bahwa darah adalah tiket VIP ke surga dunia.
Penutup: Dunia Tanpa Mitos Darah?
Mungkin utopia sejati adalah dunia di mana silsilah berhenti menjadi senjata, di mana manusia dinilai dari apa yang mereka ciptakan, bukan dari siapa yang mengalir dalam pembuluh darah mereka.
Tapi mungkin itu terlalu naif.
Selama manusia lebih suka dongeng daripada kerja keras, selama ada kursi empuk yang bisa diwariskan tanpa pertarungan, darah suci akan tetap menjadi bisnis keluarga yang paling menguntungkan.
Karena pada akhirnya, apa yang lebih memabukkan daripada berpikir bahwa kemuliaan bisa diwariskan seperti furnitur tua?
Dan bukankah, dalam relung terdalam, kita semua sedikit berharap bahwa kita juga, entah bagaimana, punya darah seorang pahlawan mengalir dalam nadi kita — meskipun yang lebih sering mengalir hanyalah kopi sachet dan sedikit kemalasan?