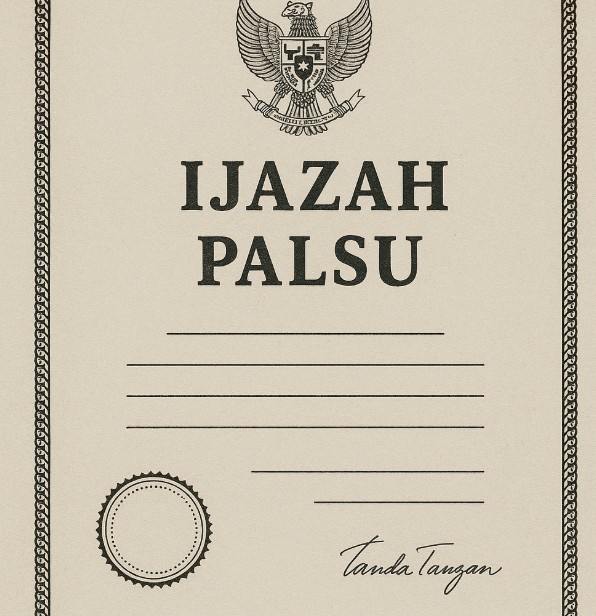Dalam debat tentang keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, dua kubu saling berhadap-hadapan seperti dalam tragedi Yunani: yang satu berdiri di atas klaim otoritas formal, yang satu lagi bertumpu pada skeptisisme publik. Tapi keduanya—yang percaya dan yang meragukan—mungkin terperangkap dalam jebakan yang sama: menyangka bahwa selembar ijazah adalah esensi dari legitimasi seorang pemimpin.
Padahal, seperti yang pernah dikatakan Michel Foucault, “Di bawah wacana tentang kebenaran, selalu tersembunyi relasi kuasa.” Dan ijazah, dalam konteks ini, adalah objek semiotik—penanda yang lebih sarat makna politis ketimbang nilai akademis.
1. Legitimasi: Ijazah sebagai Tanda, Bukan Hakikat
Dalam dunia modern, ijazah adalah instrumen administratif yang mewakili pengalaman belajar. Tapi secara filosofis, terutama sejak Derrida memperkenalkan gagasan tentang différance, kita tahu bahwa makna selalu tertunda. Teks tidak pernah sepenuhnya hadir—termasuk teks legal bernama ijazah.
Orang-orang yang membela Jokowi dengan dalih “ijazahnya sudah diverifikasi KPU” sesungguhnya sedang menjadikan simulakra (Baudrillard) sebagai pengganti realitas. Apa yang diverifikasi bukan proses belajar, tapi reifikasi administratif—selembar kertas dengan tanda tangan dan logo.
Dalam konteks ini, bahkan bila ijazah itu otentik secara fisik, tetap ada celah epistemologis: apa yang dijamin bukan kualitas, bukan intelektualitas, melainkan kepatuhan terhadap prosedur.
Maka yang dibela para loyalis bukanlah kebenaran, melainkan proseduralitas.
2. Skeptisisme: Masyarakat sebagai Penganut Pascalian
Sementara itu, kelompok yang meragukan ijazah Jokowi kerap berdiri di atas etika keraguan, seakan menjadi penerus Descartes: dubito, ergo sum. Tapi sayangnya, sebagian besar dari mereka tak berhenti pada keraguan metodologis, melainkan terperangkap dalam semangat Pascalian—yakni kepercayaan bahwa lebih baik berjaga-jaga atas kemungkinan terburuk, walau tanpa bukti mutlak.
Dengan kata lain, “Kalaupun salah, lebih baik curiga, siapa tahu benar palsu.” Maka argumen mereka berputar di sekitar gejala: jenis font, ketidakhadiran foto, absennya saksi—tanpa mampu menembus ke tataran struktur.
Lalu mereka lupa bahwa keraguan bukanlah kebenaran. Keraguan hanya sah sejauh ia terbuka terhadap penyanggahan—tapi dalam banyak kasus, para skeptik ini justru menolak semua klarifikasi dengan label “setting-an”.
Inilah bentuk kebalikan dari dogma birokrasi: dogma anti-institusi yang sama tidak rasionalnya.
3. Apa yang Lebih Palsu dari Ijazah? Demokrasi itu Sendiri
Jika kita mengikuti alur pemikiran Jean Baudrillard, kita akan sampai pada satu paradoks: bukan ijazah yang palsu, melainkan kenyataan yang telah digantikan oleh hiperrealitas. Demokrasi hari ini adalah pertunjukan: rakyat memilih berdasarkan ilusi pilihan, kandidat dipilih berdasarkan penampilan, dan legitimasi dibangun dari dokumen.
Baudrillard menulis: “Simulasi bukan tiruan realitas, ia adalah kebenaran yang dibunuh dan digantikan dengan tanda.”
Dan ijazah adalah tanda tertinggi dari sistem meritokrasi palsu. Ia tidak lagi menunjukkan proses belajar, tapi merupakan paspor ke tangga kekuasaan. Maka ketika kita memperdebatkan keaslian ijazah, kita sejatinya sedang memperdebatkan: apakah kita masih percaya bahwa sistem ini bekerja?
Jika iya, maka kita percaya bahwa negara akan memastikan hanya orang yang sah yang bisa memimpin. Jika tidak, maka kita harus mengakui bahwa sejak awal, kita semua bermain di panggung kebohongan struktural.
4. Moralitas Publik: Antara Kecurigaan dan Ketulusan
Pertanyaan pentingnya bukan: “Asli atau palsu?” tetapi: “Kenapa kita tidak bisa percaya, bahkan ketika kebenaran ditunjukkan?”
Di sinilah kita menyentuh wilayah ethos publik. Heidegger menyebut ini sebagai Vergessenheit—lupa akan hakikat. Kita telah melupakan makna dari sebuah pemimpin. Yang kita harapkan darinya bukan lagi kebijaksanaan, integritas, atau kedalaman visi, tetapi kelengkapan dokumen dan kemampuan tampil di media.
Masyarakat yang terlalu mudah mencurigai akan kehilangan kapasitas untuk merawat kepercayaan; tapi masyarakat yang terlalu mudah percaya akan menyerahkan dirinya pada tirani administratif.
5. Kesimpulan: Republik Kita, Republik Berkas
Dari kedua belah pihak—yang membela dan yang mencurigai—tak satupun bertanya soal hal yang lebih mendasar: bagaimana sistem kita bisa sampai ke titik ini, di mana semua nilai disubstitusi oleh dokumen?
Nietzsche sudah memperingatkan: “Semua konsep moral hanyalah ilusi bila tak ada keberanian untuk memeriksanya.” Tapi keberanian ini tak cukup hanya dengan menggugat, atau membela. Ia harus juga dibarengi dengan refleksi struktural: mengapa rakyat tidak percaya pada pemimpinnya sendiri? Mengapa negara tidak mampu menjawab pertanyaan rakyatnya dengan ketelanjangan yang membebaskan?
Mungkin ijazah itu asli. Mungkin juga tidak. Tapi satu hal yang jelas: baik kebenaran maupun kebohongan telah kehilangan daya kejutan dalam republik ini—karena kita telah terbiasa hidup dalam dokumentasi yang dibingkai rapih tapi hampa makna.
Dan kita semua, dengan cara kita sendiri, turut menyusun kebohongan itu—baik dengan diam, dengan curiga, atau dengan dokumen.