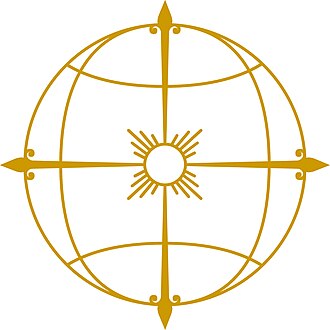Di tengah hiruk-pikuk perebutan identitas dan simbol warisan suci, ada satu warisan yang justru dibiarkan sunyi—tanpa pembela, tanpa teks kanonik, tanpa liturgi resmi. Ia tidak menyodorkan surga atau neraka, tidak pula mewajibkan kiblat tertentu. Namun dari rahimnya lahir kebudayaan, sistem nilai, dan tata hidup orang Nusantara jauh sebelum kitab-kitab besar tiba dari tanah asing. Kita menyebutnya: Kapitayan.
Kapitayan bukanlah agama dalam definisi Barat—ia tak memiliki nabi, tak mengenal dogma tertulis, dan tidak memaksakan keselamatan universal. Ia lebih mirip dengan apa yang disebut oleh Mircea Eliade sebagai hierophany—pengalaman tentang yang sakral dalam keseharian. Dalam tradisi Kapitayan, segala sesuatu yang “ada” (tan) berkelindan dalam keheningan dan kehampaan yang melingkupi—bukan ketiadaan nihilistik, melainkan kawruh tentang Sangkan Paraning Dumadi, asal-usul dan tujuan keberadaan.
Kata taya dalam Kapitayan menjadi konsep kunci. Ia bukan sekadar “tidak ada”, tetapi lebih mendekati konsep sunyata dalam Buddhisme atau la syay’ dalam tasawuf Ibn ‘Arabi. Ia menunjuk pada kekosongan primordial yang melampaui batas dikotomi ada-tiada. Kapitayan tak menyembah bentuk, karena bentuk adalah bias. Ia menyapa kekosongan, karena di situlah semua kemungkinan berdiam. Tak heran, pemujaan dilakukan di sanggar pamujan, ruang terbuka tanpa patung, tanpa gambar, tanpa nama. Hanya ada tu (hulu), hyang (energi), dan rasa (kesadaran)—sebuah trinitas kosmik yang menggetarkan.
Jika kita membuka lembaran awal peradaban Nusantara, dari Talang Tuo hingga Prasasti Ciaruteun, kita tidak menemukan nama-nama dewa seperti dalam Mahabharata. Kita justru menemukan istilah seperti Dewata Mulya Raya, Sang Hyang Taya, atau Manikmaya—yang semuanya menunjuk pada suatu prinsip kosmik, bukan entitas personal. Kapitayan tidak mempersonifikasikan Yang Mahatinggi, karena personifikasi adalah reduksi. Kapitayan memilih diam dan getar. “Tak perlu kau sebut nama-Nya. Cukup kau rasa saat embun menyentuh tanah, saat angin menggoyang padi,” bisik para resiguru di dusun-dusun yang kini telah hilang dari peta.
Dalam logika Kapitayan, manusia bukan pusat, tapi simpul. Ia bukan khalifah, bukan bayangan Tuhan, melainkan bagian dari jejaring kehidupan yang setara dengan pohon, sungai, dan batu. Urip iku mung mampir ngombe, bukan karena hidup tak penting, tapi justru karena ia begitu rapuh sehingga tak boleh dilekatkan pada ego. Maka dalam ritus Kapitayan, yang disembah bukan dewa-dewa langit, tapi roh kebersamaan: lembayung senja, hawa hangat dari tungku kayu, wangi kemenyan yang menyatu dalam napas semesta. Semuanya simbol, bukan objek kultus.
Kita bisa menganggap Kapitayan sebagai bentuk awal dari ekofenomenologi: kesadaran bahwa yang ada bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dialami. Seperti dikatakan oleh Heidegger dalam Bauen, Wohnen, Denken, manusia sejatinya dwells—menetap, bukan mendominasi. Kapitayan mengajarkan hal serupa jauh sebelumnya: tata titi tentrem, hidup selaras tanpa menggusur. Bukan hanya secara ekologis, tapi juga secara eksistensial. Tidak ada upaya menjelaskan dunia, apalagi menaklukkannya. Yang ada adalah hidup di dalamnya, dengan segala ketakterdugaan.
Namun kemudian datang masa yang lebih “terang”. Masa ketika kebenaran harus punya kitab, ketika ibadah harus punya waktu dan arah, dan ketika keyakinan harus punya nama resmi. Kapitayan, yang tak sempat mencatat dirinya, dipaksa mundur. Ia tak bisa menjawab logika kolonial yang memerlukan hukum tertulis. Ia tak bisa menjawab teologi semitik yang mencari pencipta personal. Ia pun disapu dalam sunyi. Dicap animisme oleh sarjana Barat, dikelirukan sebagai penyembah arwah oleh kaum beragama, dan dijadikan kearifan lokal oleh pemerintah yang memelihara toleransi seperti menjaga akuarium.
Padahal Kapitayan adalah kosmologi, bukan hanya kebudayaan. Ia adalah filsafat hidup yang menolak dikotomi roh-materi, dunia-akhirat, bahkan benar-salah. Ia tidak menolak pertanyaan metafisik, tapi menawarnya dengan keheningan. “Mengapa kita ada?” tanya filsuf Yunani. “Karena embun turun,” jawab petani tua dari lereng Lawu.
Hari ini, ketika dunia kembali mencari makna di tengah kerusakan lingkungan, polarisasi identitas, dan kekosongan spiritual modern, Kapitayan seharusnya hadir kembali—bukan sebagai agama baru, tapi sebagai laku hidup: eling lan waspada, sadar dan awas. Di luar sana, dunia mendewakan algoritma, dan mengukur nilai dari engagement. Tapi Kapitayan mengingatkan: apa yang paling hakiki justru tidak bisa dihitung—seperti bisikan daun pada malam hari, atau kecemasan anak kecil yang bertanya tentang kematian tanpa kata.
Barangkali inilah saatnya kita mendengarkan kembali Kapitayan—bukan untuk dikodifikasi menjadi agama resmi, tapi untuk dibiarkan seperti semula: cair, tak bernama, dan hidup dalam tubuh kolektif para penjaga tanah. Seperti dikatakan oleh Deleuze, “yang minor bukan yang kecil, tapi yang mengguncang sistem besar dari dalam.” Kapitayan adalah minor yang sabar. Ia tidak melawan dengan argumen, tapi dengan ketekunan arkais: membakar kemenyan, menanam padi, merawat pusaka, menyambut angin.
Jika para filsuf Barat sibuk merumuskan etika baru untuk masa depan planet, Kapitayan sejak awal telah mengajarkannya—tanpa konsep, tanpa istilah, hanya lewat laku. Ia bukan sistem kepercayaan, tapi sistem keberadaan. Maka, menyebut Kapitayan sebagai “pra-agama” adalah kesalahan besar. Ia bukan pra, tapi meta. Ia melampaui bentuk-bentuk agama yang datang kemudian. Ia adalah napas panjang yang menghubungkan batu dengan bintang, air dengan air mata, dan tubuh dengan tanah.
Di akhir tulisan ini, aku tak ingin mengajakmu mempelajari Kapitayan sebagai objek. Tapi resapilah ia sebagai cara hidup. Jika kau masih bisa duduk diam di bawah pohon tua, mendengar desir angin dan gemerisik daun, lalu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang lebih besar, mungkin itulah Kapitayan yang menyapamu. Tanpa nama. Tanpa janji. Tapi dengan kehadiran yang tenang dan tak terbantahkan.